
Jakarta, Redaksi Media Farkes-R – Di era ekonomi yang serba gesit dan membutuhkan fleksibilitas tinggi, praktik alih daya atau outsourcing kian menjamur di berbagai sektor industri Indonesia. Janji efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan untuk fokus pada bisnis inti menjadi daya tarik utamanya. Namun, di balik efisiensi itu, muncul suara-suara kritis yang mempertanyakan: Apakah praktik alih daya ini diam-diam tengah menggerogoti fondasi unik hubungan kerja di Indonesia, yaitu Hubungan Industrial Pancasila (HIP)?
Hubungan Industrial Pancasila bukanlah sekadar teori di atas kertas. Ia digagas sebagai landasan hubungan harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila seperti kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Ini adalah model yang menekankan kebersamaan, jaminan kerja, dan rasa memiliki dalam satu 'rumah besar' perusahaan.
Jembatan yang Renggang: Outsourcing vs. Nilai HIP
Kontras dengan semangat HIP yang mengusung kebersamaan jangka panjang layaknya sebuah keluarga, praktik alih daya seringkali menciptakan jarak. Pekerja alih daya secara hukum adalah karyawan perusahaan penyedia jasa (vendor), bukan perusahaan pengguna jasa (user). Ini menimbulkan beberapa persoalan pelik:
- Kerapuhan Jaminan Kerja: Pekerja alih daya seringkali terikat kontrak jangka pendek, bergantung pada kelangsungan kontrak antara perusahaan user dan vendor. Rasa aman dan kepastian kerja yang menjadi salah satu elemen penting dalam HIP menjadi sulit terwujud. Ini berbeda dengan semangat HIP yang mendorong hubungan kerja yang langgeng dan stabil.
- Kesenjangan Kesejahteraan: Meskipun bekerja di lingkungan yang sama, seringkali terdapat disparitas signifikan dalam hal upah, tunjangan, fasilitas, bahkan perlakuan antara pekerja tetap perusahaan user dan pekerja alih daya. Kesenjangan ini jelas kontradiktif dengan prinsip keseimbangan hak, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang diamanatkan HIP.
- Mengikis Rasa Memiliki dan Kekeluargaan: Pekerja alih daya bisa merasa seperti 'orang luar' di tempat mereka bekerja sehari-hari. Kurangnya integrasi ke dalam budaya perusahaan user, keterbatasan akses terhadap program pengembangan karier, serta minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum-forum internal perusahaan pengguna, secara langsung melemahkan semangat kekeluargaan dan rasa memiliki yang menjadi ruh HIP.
- Kompleksitas Dialog Sosial: Hubungan industrial menjadi lebih rumit karena melibatkan tiga pihak (pekerja, perusahaan vendor, dan perusahaan user). Proses dialog, perundingan, atau penyelesaian sengketa menjadi tidak sederhana, berpotensi melemahkan posisi tawar pekerja dan mengaburkan tanggung jawab.
Lanskap Hukum yang Berubah: Dari Pembatasan ke Kelonggaran?
Secara hukum, praktik alih daya di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sebelum diamandemen, dalam Pasal 64, 65, dan 66, secara spesifik membatasi alih daya hanya pada pekerjaan penunjang atau non-inti, serta mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja jika terjadi pergantian vendor. Pasal-pasal ini (terutama Pasal 65 dan 66) pada masanya dianggap upaya untuk melindungi pekerja alih daya dan memastikan mereka tidak digunakan untuk pekerjaan inti yang seharusnya diisi oleh pekerja tetap.
Namun, lanskap ini berubah drastis dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam PP 35/2021, ketentuan mengenai pembatasan alih daya pada pekerjaan non-inti dihapus. Artinya, praktik alih daya kini bisa dilakukan untuk hampir semua jenis pekerjaan, sepanjang memenuhi persyaratan perlindungan kerja yang diatur dalam PP tersebut, seperti pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi penggantian perusahaan alih daya (Pasal 19 PP 35/2021).
Secara eksplisit, hukum mencoba memberikan perlindungan minimal bagi pekerja alih daya melalui PP 35/2021. Namun, semangat undang-undang yang kini lebih fleksibel dalam hal jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, secara implisit membuka ruang praktik yang berpotensi jauh dari idealisme HIP. Ketiadaan batasan jenis pekerjaan membuat model hubungan kerja berdasarkan "keluarga besar di satu perusahaan" semakin sulit diterapkan pada unit-unit kerja yang diisi oleh pekerja alih daya.
Dilema dan Tantangan ke Depan
Situasi ini menghadirkan dilema: di satu sisi, fleksibilitas alih daya memang dibutuhkan agar dunia usaha bisa bergerak lincah dan bersaing. Di sisi lain, ekspansi praktik alih daya tanpa pengawasan ketat dan komitmen kuat terhadap prinsip HIP berisiko menciptakan kelas pekerja 'dua lapis' dengan hak dan perlindungan yang berbeda, mengikis kebersamaan, dan pada akhirnya melemahkan fondasi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sesuai amanat Pancasila.
Tantangan besar kini terletak pada implementasi dan pengawasan. Regulasi dalam PP 35/2021 yang mensyaratkan pengalihan perlindungan hak pekerja saat pergantian vendor harus benar-benar dijalankan. Lebih dari itu, baik pengusaha user maupun vendor perlu menumbuhkan kesadaran bahwa pekerja alih daya bukanlah sekadar 'tenaga kerja sewaan' yang bisa diperlakukan berbeda, melainkan bagian integral dari proses produksi atau layanan yang turut berkontribusi pada kemajuan perusahaan.
Membangun kembali jembatan yang renggang antara fleksibilitas alih daya dan idealisme HIP membutuhkan upaya bersama. Dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci. Pengawasan ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta komitmen pengusaha untuk tetap mengedepankan kesejahteraan dan martabat pekerja – siapa pun perusahaan yang menggaji mereka – adalah prasyarat mutlak agar janji efisiensi alih daya tidak dibayar mahal dengan terkikisnya nilai-nilai luhur Hubungan Industrial Pancasila di negeri ini.
Alih daya mungkin adalah keniscayaan di era modern, namun menjaga agar ia tidak menjadi 'pisau bermata dua' yang menggerogoti sendi-sendi kekeluargaan dan keadilan dalam dunia kerja adalah tanggung jawab kita bersama, demi kelangsungan Hubungan Industrial Pancasila yang kokoh.
Baca juga : Serial Dialog Imajiner, Ketika H. Fakhrudin, bangkit dari alam Fana dan bahas wacana penghapusan outsourcing disni
Bidang Advokasi FSP FARKES-R
Tim Media FSP FARKES-R




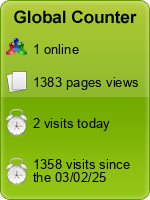




0 Komentar