Wejangan Abadi Sang Bapak Pers:
Sebuah Dialog Imajiner untuk Perjuangan Buruh di Era Digital
Di
sebuah ruang teduh yang seolah tak tersentuh waktu, aroma kopi tubruk berpadu
dengan bau kertas-kertas tua. Di sanalah Pak Sidodadi dan Rama Jaka Kustika
dari Bidang Media FSP FARKES REFORMASI duduk berhadapan dengan sosok yang
mereka kagumi hanya dari buku-buku sejarah: Raden Mas Tirto Adhi Soerjo.
Sosoknya tenang, sorot matanya tajam menembus zaman, seolah ia baru saja
meletakkan penanya setelah menulis tajuk rencana untuk Medan Prijaji.
"Jadi,
Tuan-tuan berdua ini adalah juru warta dari kaum buruh di zaman yang katanya
serba cepat?" Tirto membuka percakapan, suaranya berat dan berwibawa.
Sidodadi,
yang lebih senior, mengangguk hormat. "Benar, Eyang Tirto. Kami datang
karena merasa gagap. Informasi begitu melimpah, perhatian orang begitu mudah
teralihkan. Suara kami, suara buruh, seringkali tenggelam dalam kebisingan
media sosial. Kami ingin belajar dari Eyang, bagaimana kekuatan pena bisa
membangkitkan kesadaran, seperti yang Eyang lakukan dulu."
Tirto
tersenyum tipis, lalu menyesap kopinya. "Medan perang kita mungkin
berbeda, tapi senjatanya tetap sama: cerita
yang menyentuh nurani. Kalian jangan keliru, Tuan-tuan. Dulu,
saya tidak sekadar menulis bahwa rakyat Hindia menderita. Itu fakta dingin yang
mudah dilupakan. Saya menuliskan bagaimana
mereka menderita."
"Saya
kisahkan tentang petani di Lebak yang punggungnya melengkung karena memikul
hasil bumi untuk para pejabat kompeni, sementara anaknya kelaparan di rumah.
Saya tuliskan rintihan para kuli kontrak di Deli yang cambuk mandor terasa
lebih perih daripada sengat matahari. Saya tidak menjual angka atau statistik,
saya menjual rasa sakit,
kemarahan, dan harapan yang terampas. Tulisan itu harus menjadi
cermin bagi pembaca, agar mereka melihat ketidakadilan itu menimpa saudara
sebangsanya, dan bisa saja menimpa diri mereka sendiri."
Rama,
yang lebih muda dan memegang gawai di tangannya, menyela dengan sopan.
"Kami mengerti, Eyang. Tapi bagaimana menerjemahkannya ke zaman sekarang?
Isu kami kompleks: kerja prekariat, gig
economy, upah yang tak layak, bahkan kini ada isu perubahan iklim
dan just transition."
Tirto
meletakkan cangkirnya. Matanya berkilat, seolah melihat medan juang yang baru.
"Bagus!
Itu artinya penderitaan rakyat hanya berganti rupa. Maka, inilah peta jalan
yang bisa kalian tempuh. Dengarkan baik-baik."
Peta Jalan Publikasi Media Gerakan
Buruh ala Tirto Adhi Soerjo
Langkah
Pertama: Identifikasi "Luka Zaman" dan Beri Nama yang Menggugah
"Kalian
menyebutnya 'kerja prekariat' atau 'gig
economy'. Itu istilah kaum terpelajar. Rakyat biasa tidak
merasakannya. Kalian harus memberinya nama yang lebih menusuk. Sebutlah 'Perbudakan Digital'
atau 'Kerja Rodi Gaya
Baru'. Gunakan istilah yang membangkitkan memori kolektif
tentang penindasan."
"Jangan
hanya bicara soal algoritma yang tidak adil. Ceritakan tentang seorang
pengemudi ojek online, sebut saja namanya Budi. Kisahkan bagaimana ia menatap
layar gawainya berjam-jam di pinggir jalan, menanti orderan yang tak kunjung
datang, sementara di rumah anaknya butuh susu. Buat pembaca merasakan kecemasan
Budi setiap kali notifikasi berbunyi, dan kekecewaannya saat itu bukan orderan.
Itulah cultuurstelsel
zaman kalian: kerja keras tanpa kepastian hasil."
Langkah
Kedua: Personifikasi Perjuangan, Ciptakan Pahlawan Keseharian
"Jangan
tampilkan buruh sebagai korban yang pasrah. Tampilkan mereka sebagai pejuang.
Dulu, saya mengangkat kisah para priyayi yang tercerahkan dan berani melawan.
Sekarang, angkatlah kisah seorang buruh pabrik perempuan yang berani
mengorganisir kawan-kawannya untuk menuntut hak cuti haid. Ceritakan tentang
seorang pekerja kontrak yang diam-diam belajar hukum perburuhan di malam hari
untuk melawan PHK sepihak."
"Jadikan
mereka simbol. Kisah mereka adalah amunisi. Satu kisah inspiratif lebih kuat
dari seratus rilis pers yang kaku. Publik harus melihat wajah di balik angka
statistik, melihat denyut nadi di balik setiap tuntutan."
Langkah
Ketiga: Bangun Narasi Besar yang Menghubungkan Semua Titik
"Ini
yang paling penting," kata Tirto, mencondongkan tubuhnya ke depan.
"Jangan biarkan isu-isu itu berdiri sendiri. Kalian harus merangkainya
menjadi sebuah narasi besar. Hubungkan titik-titiknya."
"Begini
caranya: Kisah Budi si 'budak digital' tadi, terhubung dengan kisah buruh
pabrik garmen yang di-PHK karena pabriknya beralih ke mesin. Keduanya adalah
korban dari sistem ekonomi yang memuja efisiensi di atas kemanusiaan. Lalu,
hubungkan lagi dengan isu yang lebih besar."
"Kalian
bicara soal perubahan iklim dan just
transition? Sempurna! Ceritakan bagaimana pabrik yang sama, yang
mem-PHK buruhnya, juga membuang limbah ke sungai tempat anak-anak Budi bermain.
Maka, perjuangan menuntut upah layak adalah perjuangan untuk udara bersih.
Perjuangan melawan PHK sepihak adalah perjuangan untuk transisi yang berkeadilan,
di mana peralihan ke energi hijau tidak boleh mengorbankan buruh menjadi
tumbal."
"Narasi
besarnya adalah: Kesejahteraan
Buruh adalah Kesejahteraan Bumi. Keadilan untuk Pekerja adalah Keadilan untuk
Masa Depan. Dengan begitu, kalian tidak hanya bicara pada
buruh, tapi juga pada aktivis lingkungan, mahasiswa, dan kelas menengah yang
peduli pada masa depan anak-anaknya."
Langkah
Keempat: Kuasai Medan Perang Digital dengan Konsistensi
"Dulu,
saya hanya punya koran. Kalian punya puluhan 'koran' di genggaman kalian.
Gunakan semuanya, tapi dengan strategi."
- Media
Sosial (TikTok, Instagram): Gunakan untuk 'tusukan' cepat.
Video pendek satu menit tentang wajah lelah Budi, kutipan kuat dari buruh
perempuan yang berani melawan. Tujuannya bukan penjelasan mendalam, tapi
membangkitkan empati
dan kemarahan dalam sekejap.
- Situs
Web/Blog Serikat: Ini adalah Medan Prijaji kalian.
Di sinilah kalian muat tulisan-tulisan mendalam. Analisis kebijakan,
investigasi kondisi pabrik, dan kisah-kisah pahlawan keseharian tadi
secara utuh. Ini untuk membangun kredibilitas
dan pemahaman.
- Podcast:
Ini adalah mimbar kalian. Undang buruh untuk bercerita langsung. Biarkan
publik mendengar suara mereka yang bergetar karena marah, atau tawa mereka
yang penuh harapan. Suara manusia punya kekuatan yang tak bisa ditandingi
tulisan. Ini untuk membangun koneksi
emosional.
"Dan
yang terpenting," Tirto menekankan, "adalah konsistensi. Terbitkan
tulisan setiap hari, setiap minggu. Seperti air yang menetes terus-menerus di
atas batu, lambat laun batu sekeras apa pun akan berlubang. Teruslah bercerita,
teruslah mengabarkan, jangan biarkan api ini padam."
Sidodadi
dan Rama terdiam, meresapi setiap kata. Wajah mereka yang semula bingung kini
memancarkan pencerahan. Mereka tidak lagi melihat tumpukan isu yang rumit,
melainkan sebuah jalinan cerita perjuangan yang siap untuk dikisahkan.
"Pena
kalian, atau 'keyboard' seperti yang kalian sebut," Tirto menutup
wejangannya sambil tersenyum, "adalah alat untuk membuka mata mereka yang
tertidur, menyatukan mereka yang tercerai-berai, dan memberikan suara pada
mereka yang dibungkam. Dulu musuh saya adalah kebodohan dan kekuasaan kolonial.
Musuh kalian adalah apatisme
dan ketidakadilan yang dibungkus kemajuan zaman. Tugas kalian
sama dengan tugas saya: menulis kebenaran, segetir apa pun rasanya, hingga
fajar keadilan itu terbit."
Sosok
Tirto Adhi Soerjo perlahan memudar, meninggalkan aroma kopi dan semangat yang
membara di dalam dada Sidodadi dan Rama. Mereka kini tahu, perjuangan di era
digital bukanlah tentang algoritma atau jumlah penonton, melainkan tentang
menemukan kembali kekuatan paling purba dari sebuah pergerakan: kekuatan cerita
yang mampu mengubah dunia.
Jakarta 06 September 2025
Disarikan dari Notulensi Rapat Kontributor Media FSP FARKES-R





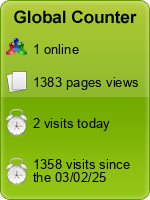





0 Komentar