- PENDAHULUAN
- Visi Integralistik 1960: Kapsul Waktu dari Era Perencanaan Luhur
- Arsip Nasional : Artikel Mengenai Semesta Berencana
- Indonesia Kontemporer: Negeri di Persimpangan Geopolitik dan Ekonomi Pasar
- Sektor Tenaga Kerja: Pilar Rapuh di Bawah Beban Kontradiksi
- Geopolitik Kontemporer dan Dampaknya pada Pilar Tenaga Kerja
- Menarik Garis Kritis: Ke Mana Arah Pembangunan Kita?
Perrnahkah terbayang sebuah negara merancang pembangunan yang tidak parsial, melainkan menyentuh setiap sudut kehidupan dan mengarahkannya secara terintegrasi dan terencana demi satu cita-cita luhur? Itulah inti dari Pembangunan Semesta Berencana, konsep fundamental yang menjadi pedoman awal Indonesia dalam upaya ambisius mewujudkan masyarakat adil dan makmur berbasis Pancasila, sebuah visi pembangunan yang benar-benar mencakup "semesta" kebangsaan.
PENDAHULUAN
Enam dekade lebih telah berlalu sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 menggariskan "Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969". Frasa kunci di dalamnya - Pembangunan Semesta Berencana - bukan sekadar deret kata teknokratis, melainkan cerminan ambisi besar sebuah bangsa yang relatif baru melepaskan diri dari belenggu kolonial: membangun secara "menyeluruh" dan "berencana" untuk mencapai "masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila". Ini adalah tonggak kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif, sebuah visi yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berakar pada ideologi fundamental.
Namun, sejarah mencatat, visi agung tersebut tak sempat terimplementasi dengan baik. Badai geopolitik regional (Trikora, Dwikora) dan gejolak internal (pemberontakan G30S/PKI) menggagalkan momentum awal pembangunan terencana tersebut. Ironisnya, meski gagal dieksekusi secara paripurna dalam rentang waktu yang ditetapkan, Tap MPRS ini tetap diakui sebagai penanda kesadaran akan perlunya perencanaan pembangunan nasional. Sebuah kesadaran yang, patut dipertanyakan, seberapa dalam dan konsisten terejawantah dalam praktik pembangunan di era pasca-Orde Baru, bahkan hingga hari ini.
Tulisan opini ini, sebagai sebuah otokritik dan perenungan historis. Kita akan membandingkan esensi idealisme "Pembangunan Semesta Berencana" tahun 1960-an – yang bertekad menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui perencanaan menyeluruh – dengan realitas sosial-ekonomi Indonesia kontemporer. Perbandingan ini akan kita tarik melalui lensa spesifik namun krusial: kondisi ketenagakerjaan, tingginya angka pengangguran, carut-marut penegakan hukum perburuhan, dan relasi industrial buruh-pengusaha yang rapuh. Sektor tenaga kerja, yang seharusnya menjadi tulang punggung dan penerima manfaat utama dari pembangunan menuju "adil dan makmur", justru kerap menjadi arena kontestasi, eksploitasi, dan ketidakpastian.
Bagaimana visi 1960 berhadapan dengan kenyataan 2020-an yang diwarnai dinamika geopolitik global yang kian kompleks?
Visi Integralistik 1960: Kapsul Waktu dari Era Perencanaan Luhur
Mari sejenak kembali ke tahun 1960. Indonesia, di bawah kepemimpinan Soekarno, tengah merumuskan fondasi negara bangsa yang mandiri dan berdaulat penuh. Konteks global adalah era Perang Dingin, di mana pilihan ideologi dan model pembangunan menjadi sangat relevan. Tap MPRS II/1960 muncul dari semangat percaya diri untuk merancang nasib bangsa sendiri, menolak ketergantungan total pada kekuatan asing, dan mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam Pancasila.
"Semesta Berencana" mengandung makna filosofis yang dalam. "Semesta" berarti meliputi seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan). "Berencana" menyiratkan bahwa pembangunan bukan sesuatu yang dibiarkan terjadi begitu saja oleh mekanisme pasar atau kekuatan sporadis, melainkan diarahkan secara sadar, terintegrasi, dan bertahap oleh negara sebagai representasi kolektif bangsa. Tujuannya jelas: masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan pembangunan yang berkeadilan, merata, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.
Dalam visi ini, sektor tenaga kerja tentu bukan sekadar faktor produksi semata. Tenaga kerja adalah subjek pembangunan, elemen kunci dalam mencapai kemakmuran, dan penerima manfaat utama dari keadilan sosial. Pembangunan yang "menyeluruh" mau tidak mau harus mencakup perlindungan, peningkatan kualitas, dan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja. Pengangguran adalah anomali yang harus ditangani secara sistemik dalam kerangka perencanaan nasional.
Gagalnya implementasi Tap MPRS 1960 memang lebih disebabkan oleh faktor politik dramatis pada masanya.
Namun, benih kesadaran akan pentingnya perencanaan komprehensif telah ditanam. Pertanyaannya hari ini: Apakah spirit komprehensif, berencana, dan berkeadilan yang berakar pada Pancasila itu masih hidup dalam praktik pembangunan kita, terutama ketika kita berhadapan dengan realitas yang jauh lebih kompleks dan terintegrasi secara global?
 |
| Arsip Nasional : Artikel Mengenai Semesta Berencana |
Indonesia Kontemporer: Negeri di Persimpangan Geopolitik dan Ekonomi Pasar
Lompatan waktu ke era saat ini membawa kita pada lanskap yang sangat berbeda. Indonesia telah melewati era Orde Baru dengan model pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan integrasi ke pasar global. Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, namun juga mewariskan tantangan struktural, termasuk dalam ekonomi.
Kondisi nasional hari ini ditandai oleh paradoks. Di satu sisi, Indonesia adalah anggota G20, ekonomi yang terus tumbuh (meski fluktuatif), dan pasar yang besar. Di sisi lain, kesenjangan sosial-ekonomi tetap lebar, sektor informal mendominasi, dan kualitas pekerjaan masih menjadi isu krusial. Dinamika domestik ini tak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik global yang kian bergejolak. Perang dagang antara kekuatan ekonomi besar, disrupsi teknologi (AI, otomatisasi), perubahan iklim yang menuntut transisi energi, pandemi yang merusak rantai pasok, hingga konflik regional – semuanya memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dan tentu saja, pasar tenaga kerja di Indonesia.
Dalam lanskap global yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia dituntut untuk bersaing, menarik investasi, dan memastikan stabilitas domestik. Kebijakan pembangunan seringkali (atau bahkan cenderung) merespons tekanan dan peluang dari eksternal, kadang dengan mengorbankan visi pembangunan yang berakar kuat pada nilai-nilai internal seperti keadilan sosial menyeluruh ala Pancasila dan PSB. Di sinilah letak kontras yang mencolok. Jika PSB bercita-cita merancang dari dalam untuk mencapai kesejahteraan bersama, model pembangunan kontemporer kerap terasa seperti beradaptasi dengan tuntutan dari luar demi pertumbuhan (yang diharapkan trickle down).
Sektor Tenaga Kerja: Pilar Rapuh di Bawah Beban Kontradiksi
Adalah di sektor tenaga kerja, hantu dari visi PSB dan realitas kontemporer paling kentara saling berhadapan. Tenaga kerja adalah fondasi riil dari "masyarakat yang adil dan makmur". Tanpa pekerjaan yang layak, upah yang mencukupi, dan perlindungan yang memadai, konsep keadilan dan kemakmuran hanyalah bangunan di atas pasir.
Tingginya Pengangguran dan Kualitas Kerja yang Meragukan: Meskipun angka pengangguran terbuka secara statistik telah menurun dari puncaknya pasca-pandemi, realitasnya jauh lebih kompleks. Angka tersebut seringkali tidak menangkap penuh kondisi underemployment (bekerja di bawah jam optimal atau di bawah kualifikasi) atau mereka yang putus asa mencari kerja. Lebih penting lagi, isu utamanya bukan hanya kuantitas pekerjaan, tetapi kualitas. Banyak pekerjaan yang tersedia berada di sektor informal, dengan minimnya jaminan sosial, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak aman. Pengangguran kaum muda (youth unemployment) tetap menjadi masalah struktural saking kronisnya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, atau memang ketiadaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja baru yang kian besar. Geopolitik global memperparah ini; otomatisasi yang didorong persaingan global mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, sementara transisi energi mungkin menghilangkan pekerjaan di sektor fosil tanpa menciptakan cukup pekerjaan baru yang setara di sektor energi terbarukan. Apakah ini bagian dari pembangunan yang "menyeluruh" menuju "adil dan makmur"? Data dan realitas lapangan berkata lain.
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan: Macan Kertas tanpa Taring? Indonesia memiliki perangkat hukum ketenagakerjaan yang relatif komprehensif di atas kertas, mencakup hak berserikat, upah minimum, pesangon, hingga keselamatan kerja. Namun, kesenjangan antara hukum on the book dan hukum in action sangat lebar. Penegakan hukum perburuhan dihadapkan pada berbagai tantangan:
Keterbatasan Pengawas Ketenagakerjaan: Jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Jangkauan pengawasan terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil atau sektor informal yang luas.
Korupsi dan Kolusi: Tidak bisa dipungkiri, praktik korupsi atau kolusi antara oknum pengawas dan pihak pengusaha melemahkan fungsi kontrol negara. Pelanggaran norma ketenagakerjaan seringkali 'diselesaikan' di bawah tangan. Kasus terbaru Korupsi ketenagakerjaan.
Aksesibilitas Keadilan bagi Buruh: Mengajukan gugatan terhadap pengusaha adalah proses yang panjang, mahal, dan penuh risiko bagi buruh (ancaman PHK, intimidasi). Sistem penyelesaian perselisihan industrial (PHI) seringkali lambat dan tidak memihak buruh.
Lobbying Kuat dari Pengusaha: Kepentingan bisnis memiliki daya tawar (lobbying power) yang kuat dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan, seringkali berhasil melonggarkan aturan atau membuat sanksi pelanggaran menjadi tidak efektif. Hasilnya? Hukum perburuhan terasa tumpul ketika berhadapan dengan pelanggaran sistematis oleh korporasi besar. Ini adalah antitesis dari visi negara yang merancang pembangunan untuk melindungi dan memajukan rakyatnya, termasuk pekerja.
Relasi Industrial Buruh-Pengusaha: Antagonisme dalam Balutan Keharmonisan Semu Hubungan industrial yang seharusnya harmonis dan berbasis Hubungan Industrialis Pancasila, di Indonesia seringkali bernuansa antagonistik, meskipun secara retoris selalu didorong Tripartit (pemerintah, buruh, pengusaha). Serikat pekerja, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuatan pengusaha dan sarana kolektif buruh menyuarakan aspirasi, seringkali lemah. Faktor penyebabnya beragam: fragmentasi serikat, keterbatasan sumber daya, serangan balik (employer backlash) terhadap aktivitas serikat, bahkan dugaan intervensi pihak ketiga.
Daya tawar buruh dalam perundingan upah, kondisi kerja, atau jaminan sosial sangat rendah, terutama bagi buruh tidak terampil atau yang bekerja di sektor informal dan rentan (misalnya, buruh harian lepas, buruh migran). Omnibus Law Cipta Kerja, misalnya, dilihat oleh banyak pihak (terutama buruh dan akademisi kritis) sebagai pergeseran drastis dalam relasi industrial, lebih jauh memihak kepentingan investasi dan fleksibilitas pasar kerja (yang seringkali berarti prekariat) ketimbang jaminan dan perlindungan bagi buruh. Argumentasi bahwa ini untuk menarik investasi asing dalam konteks persaingan geopolitik global, secara implisit mengorbankan visi keadilan bagi pekerja yang diamanatkan oleh Pancasila dan pernah coba dirumuskan dalam semangat PSB.
Geopolitik Kontemporer dan Dampaknya pada Pilar Tenaga Kerja
Kondisi geopolitik dunia saat ini tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga faktor pendorong degradasi conditions di sektor tenaga kerja. Persaingan antarnegara untuk menarik investasi asing langsung (FDI) seringkali menciptakan "perlombaan ke bawah" (race to the bottom) dalam standar perburuhan. Negara-negara berlomba menawarkan insentif termurah, termasuk dalam bentuk upah rendah, fleksibilitas PHK yang tinggi, dan pelonggaran aturan lingkungan/buruh, demi dianggap "ramah investasi".
Disrupsi teknologi global menuntut adaptasi masif, namun transisi ini seringkali tidak adil bagi pekerja. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital terancam tergusur tanpa adanya program upskilling atau reskilling yang memadai dan komprehensif dari negara atau industri. Perubahan rantai pasok akibat pandemi atau konflik (misalnya, perang di Eropa Timur) dapat menyebabkan PHK massal di sektor-sektor yang terkait, tanpa adanya jaring pengaman sosial yang kuat bagi pekerja terdampak.
Dalam konteks ini, negara dihadapkan pada dilema: memprioritaskan daya saing global (yang seringkali diartikan sebagai pasar kerja yang 'fleksibel') atau menegakkan perlindungan dan kesejahteraan buruh sesuai amanat konstitusi dan spirit Pancasila (yang pernah coba diwadahi dalam PSB)? Realitas menunjukkan, tarikan untuk memenangkan persaingan pasar dan investasi global seringkali lebih kuat, menyebabkan pilar tenaga kerja, yang seharusnya kokoh dalam visi pembangunan adil dan makmur, menjadi rapuh dan terpinggirkan.
Menarik Garis Kritis: Ke Mana Arah Pembangunan Kita?
Membandingkan semangat Pembangunan Semesta Berencana 1960 dengan realitas ketenagakerjaan hari ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang getir: visi pembangunan yang menyeluruh, berencana, dan berkeadilan berbasis Pancasila tampaknya semakin tergerus dalam pusaran ekonomi pasar global dan pragmatisme politik jangka pendek.
Tap MPRS 1960, meski gagal, menunjukkan bahwa di awal kemerdekaan, bangsa ini memiliki kesadaran dan ambisi untuk merancang masa depannya secara mandiri dan untuk mewujudkan keadilan sosial secara nyata bagi seluruh rakyat, termasuk buruh. Hari ini, enam dekade kemudian, di tengah pertumbuhan ekonomi dan klaim sebagai negara demokrasi, pilar tenaga kerja – fondasi riil dari masyarakat adil dan makmur – justru menunjukkan gejala-gejala seperti prekaritas yang kian meluas, perlindungan hukum yang lemah, dan relasi industrial yang timpang.
Geopolitik global menghadirkan tantangan yang berbeda dari era 1960-an. Namun, justru dalam konteks inilah, visi pembangunan yang kuat, berakar pada Pancasila, dan berpihak pada rakyat (termasuk buruh) menjadi semakin relevan dan krusial. Jika tenaga kerja, sebagai subjek dan objek pembangunan, terus-menerus dihadapkan pada ketidakpastian, eksploitasi, dan pengabaian hukum, maka cita-cita "adil dan makmur" yang termuat dalam TAP MPRS 1960 dan konstitusi kita hanya akan menjadi retorika kosong.
Indonesia hari ini membutuhkan refleksi mendalam: Apakah kita benar-benar membangun secara "semesta berencana" untuk mencapai "masyarakat yang adil dan makmur"? Atau kita hanya terseret arus global, mengorbankan nasib pilar ekonomi kita – para pekerja – demi pertumbuhan yang tidak inklusif dan keadilan yang tumpul? Hantu Pembangunan Semesta Berencana bergentayangan, mengingatkan kita pada ambisi luhur yang belum tertunaikan, terutama bagi mereka yang keringatnya menyokong ekonomi bangsa. Tugas para peneliti adalah menelaah lebih dalam mengapa kesenjangan ini terjadi dan bagaimana visi keadilan bagi buruh dapat kembali menjadi inti dari setiap rencana pembangunan nasional.
Bidang Advokasi FSP FARKES-R





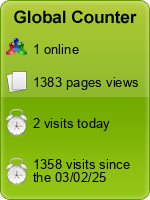





0 Komentar